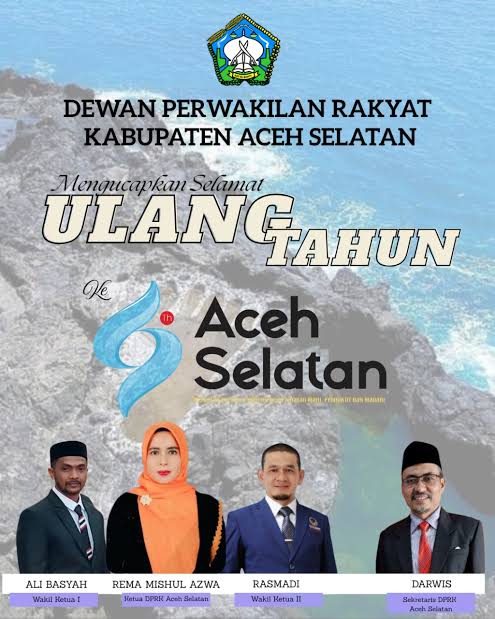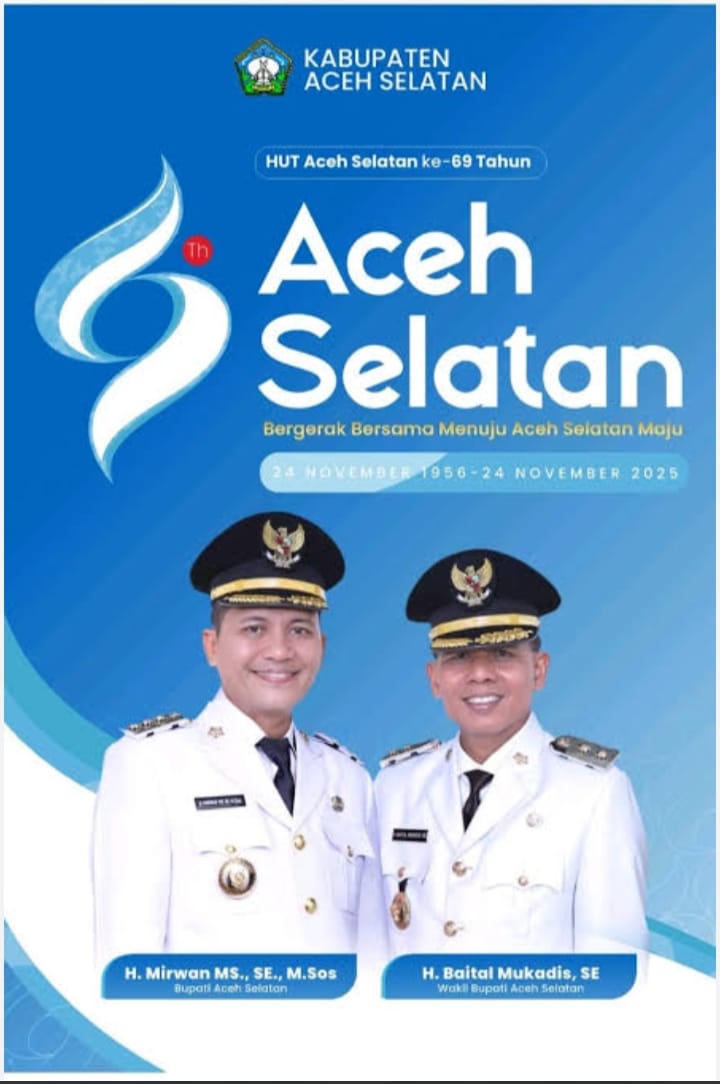Keadilan Ekologis: Menimbang Kembali Relasi Manusia, Alam, dan Pembangunan
Oleh: Teuku Muhammad Zulfikar
=====> Dalam beberapa dekade terakhir, krisis lingkungan global, mulai dari perubahan iklim, deforestasi, pencemaran air dan udara, hingga hilangnya keanekaragaman hayati telah menjadi isu sentral dalam wacana pembangunan berkelanjutan.
Namun demikian, diskursus ini sering kali terjebak dalam pendekatan teknokratis yang menitikberatkan pada solusi teknis, seraya mengabaikan dimensi keadilan sosial dan ekologis yang melekat di dalamnya. Di sinilah pentingnya gagasan keadilan ekologis (ecological justice) sebagai kerangka berpikir kritis yang memadukan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dengan pengakuan atas hak-hak komunitas manusia, terutama kelompok rentan dan makhluk hidup non-manusia.
Memahami Keadilan Ekologis
Keadilan ekologis melampaui konsep keadilan lingkungan (environmental justice) yang berfokus pada distribusi beban lingkungan secara adil antar kelompok sosial. Ia menawarkan pendekatan yang lebih holistik, yaitu dengan mengakui bahwa alam bukan sekadar sumber daya untuk dimanfaatkan manusia, tetapi juga memiliki nilai intrinsik dan hak moral untuk dilindungi.
Menurut Robyn Eckersley (1992), keadilan ekologis menuntut reformulasi hubungan manusia dengan alam—dari yang bersifat antroposentris menjadi ekosentris. Artinya, bukan hanya manusia yang menjadi subjek keadilan, melainkan juga spesies lain dan ekosistem secara keseluruhan. Pandangan ini mengajak kita untuk mempertimbangkan keadilan lintas spesies, lintas generasi, dan lintas geografis dalam kebijakan lingkungan.
Ketimpangan Ekologis sebagai Ketimpangan Sosial
Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pembangunan ekonomi yang eksploitatif terhadap sumber daya alam sering kali dilakukan atas nama “kepentingan nasional” atau “investasi strategis.” Namun dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan ini kerap meminggirkan hak-hak masyarakat adat, petani kecil, nelayan tradisional, dan komunitas lokal lainnya yang hidup selaras dengan alam. Ironisnya, mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan ekologis justru menjadi kelompok yang paling terdampak.
Misalnya, proyek tambang, perkebunan sawit, dan pembangunan infrastruktur besar kerap menyebabkan perampasan lahan, pencemaran lingkungan, hingga konflik sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan ekologis struktural, yakni ketimpangan dalam hal siapa yang menikmati manfaat ekonomi dari eksploitasi alam dan siapa yang menanggung biayanya, baik dalam bentuk kerusakan lingkungan maupun penderitaan sosial.
Secara hukum, konsep keadilan ekologis masih belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum positif Indonesia. Meski terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya seringkali lemah, terutama dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan ekologis.
Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi pernah menegaskan dalam beberapa putusan bahwa pengakuan atas hak masyarakat adat dan lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, pengakuan normatif ini belum selalu berbanding lurus dengan realitas kebijakan dan praktik di lapangan. Dalam konteks ini, dorongan untuk mengarusutamakan keadilan ekologis dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik menjadi sangat penting.
Keadilan Ekologis dan Tanggung Jawab Global
Keadilan ekologis juga berkaitan erat dengan isu global, seperti perubahan iklim. Negara-negara di belahan bumi selatan yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim, umumnya merupakan pihak yang paling sedikit menyumbang emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, negara-negara maju yang telah lama mengindustrialisasi dirinya justru menanggung tanggung jawab historis terbesar atas krisis ini.
Prinsip “common but differentiated responsibilities” (CBDR) dalam hukum lingkungan internasional merupakan upaya untuk menghadirkan keadilan ekologis di tingkat global, namun dalam pelaksanaannya sering terhambat oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi.
Mewujudkan keadilan ekologis bukan hanya soal melindungi lingkungan, tetapi juga soal mendesain ulang model pembangunan dan tata kelola sumber daya alam agar lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan. Ini menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengakuan terhadap hak-hak ekologis komunitas lokal, dan perubahan paradigma dari eksploitasi menuju koeksistensi.
Di tengah krisis iklim global dan ketimpangan sosial yang terus melebar, keadilan ekologis harus dijadikan pijakan etis dan politik dalam setiap proses pembangunan. Hanya dengan cara itulah kita bisa memastikan bahwa bumi ini tetap menjadi rumah yang layak huni, bukan hanya untuk generasi kita, tetapi juga untuk generasi mendatang dan semua makhluk hidup yang berbagi ruang dengan kita.
Penulis:
Dr. Ir. Teuku Muhammad Zulfikar, S.T., M.P., IPU. (Akademisi & Praktisi Lingkungan di Aceh)*